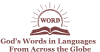45. Keluarga dan Pernikahan Bukan Lagi Tempat yang Aman Bagiku
Saat aku masih kecil, keluargaku sangat miskin. Ayahku hanya mendapat poin kerja dari tim produksi dan tidak peduli dengan urusan rumah tangga, ibuku pun tidak bisa mengandalkan ayah saat dia diperlakukan tidak adil atau menghadapi kesulitan. Dia menangani semuanya sendiri dan menanggung banyak penderitaan. Aku berpikir, "Ketika nanti aku menikah, aku harus mencari pria yang mengutamakan keluarga, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan, atau paling tidak seseorang yang akan melindungi dan membelaku saat aku mengalami kesulitan." Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Setelah menikah, aku mendapati suamiku tidak bertanggung jawab, dan dia sama sekali tidak peduli padaku, jadi mengurus anak dan mengelola rumah tangga semuanya kutangani sendiri. Kemudian, dia mulai berselingkuh di luar sana dan sering tidak pulang saat malam. Aku benar-benar tidak tahan lagi dan akhirnya kami bercerai. Setelah bercerai, hidupku terombang-ambing tanpa punya sandaran, dan merasa sangat sendirian serta tak berdaya. Aku makin merindukan rumah tangga yang stabil, juga seseorang yang bisa menolongku di saat sulit dan yang bersedia mendengarkanku. Pada tahun 2006, aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Dia adalah orang yang jujur dan baik hati, dan meskipun bukan orang kaya, dia memperlakukanku dengan sangat baik dan sangat perhatian terhadapku. Dia mau mendengarkanku, dan bahkan membantuku membayar asuransi anak perempuanku. Aku sangat tersentuh, kurasa dia orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan bisa kujadikan sandaran. Tidak lama kemudian, kami menikah. Aku sangat menghargai pernikahan ini. Untuk mendukung pendidikan anak kami, kami membuka toko kecil. Suamiku seorang pekerja keras dan cakap, apa pun yang terjadi, dia selalu turun tangan untuk mengurusnya, sehingga aku tidak pernah harus merasa khawatir atau terbebani. Aku sangat gembira, dan merasa akhirnya aku punya seseorang yang bisa kuandalkan serta rumah tangga yang stabil.
Pada tahun 2013, aku dan suamiku menerima pekerjaan Tuhan Yang Mahakuasa pada akhir zaman. Kami menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan bersama, dan aku sering berpikir, "Bagus sekali kami bisa percaya kepada Tuhan bersama, dan tidak ada yang menganiaya atau menghalangi kami! Di masa mendatang, kami berdua bisa diselamatkan." Aku sangat gembira. Namun lambat laun, aku menyadari suamiku tidak mengejar kebenaran, dia juga jarang membaca firman Tuhan dan terus-menerus terikat pada orang-orang dan hal-hal duniawi. Pada tahun 2018, suamiku berhenti percaya. Sejak saat itu, dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, dan setiap kali para saudari datang untuk pertemuan, dia selalu memasang wajah masam. Suatu kali, seorang saudari datang untuk menghadiri pertemuan, dan dia langsung melotot dan berteriak, "Apa yang kaulakukan di sini? Cepat keluar!" Saudari itu tidak punya pilihan selain segera pergi. Setelah itu, dia tidak mau mendengarkan apa pun yang kukatakan, dan karena takut membuatnya marah, aku pun berhenti berbicara. Aku membatin, "Dahulu hubungan kami sangat baik, maka sebaiknya aku tidak usah berdebat dengannya soal iman, karena bisa merusak hubungan kami." Akhirnya, pemimpin gereja harus mengatur agar aku menghadiri pertemuan di tempat lain. Terkadang, saat aku pulang terlambat dari pertemuan, wajah suamiku cemberut dan mengomel karena aku pulang terlalu larut, jadi setiap kali pergi ke pertemuan, aku selalu merasa diburu waktu. Aku takut jika dia pulang dan makanannya belum siap, dia akan jengkel.
Suatu kali saat pertemuan, pemimpin sedang bersekutu tentang firman Tuhan, awalnya aku bisa mendengarkan dengan saksama, tetapi saat mendekati jam makan dan kelihatannya dia masih belum berniat untuk selesai, hatiku mulai bergejolak, "Kenapa belum juga selesai? Lihat jam berapa ini! Aku masih harus pulang dan memasak untuk suamiku. Kalau aku pulang terlambat, kami bisa bertengkar lagi. Bukankah itu akan membuat hubungan kami makin renggang?" Aku pun menjadi sangat cemas sampai tidak bisa duduk tenang atau mendengarkan apa yang dikatakan saudari itu, dan aku pun berkata, "Sudah waktunya pulang." Saudari itu pun terpaksa mengakhiri pertemuan dengan terburu-buru. Dengan ekspresi murung, aku langsung pergi. Hampir setiap kali saat perjalanan pulang dari pertemuan, hatiku gelisah. Kalau aku pulang dan mendapati suamiku belum tiba di rumah, barulah hatiku bisa tenang, tetapi kalau dia ada di rumah, aku akan tergesa-gesa memasak dengan gugup, takut dia tidak senang. Makin aku mengalah, dia pun makin menjadi-jadi, dan kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya atau ada ucapanku yang keliru, dia akan naik pitam. Dia berkata, "Seharian kau hanya sibuk di pertemuan dan membaca firman Tuhan—apa yang bisa kuharapkan darimu? Kita tidak sejiwa dan tidak sejalan. Cepat atau lambat, kita pasti akan berpisah!" Begitu mendengar suamiku berkata bahwa kami akhirnya akan berpisah, aku takut harus hidup sendiri lagi. Namun, aku juga tidak mau meninggalkan Tuhan, dan aku sangat menderita. Aku membatin, "Kami telah bekerja keras membangun rumah tangga yang sempurna ini, dan dia juga memperlakukanku dengan cukup baik. Kalau aku benar-benar meninggalkannya, masih bisakah aku punya kehidupan seperti ini?" Demi mempertahankan keluarga kami, aku jadi makin berhati-hati. Kadang-kadang, saat suamiku bekerja, aku rela membaca firman Tuhan lebih sedikit dan malah membantunya, hanya agar dia tetap senang. Aku juga mengurus semua pekerjaan di rumah, menyiapkan tiga kali makan setiap hari sesuai seleranya, dan meskipun dia mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar, aku tidak membantah, karena aku tidak ingin memancing pertengkaran lagi.
Suatu kali, dua saudari datang ke rumah untuk membicarakan sesuatu denganku, dan suamiku bergegas menerobos keluar dari kamar lalu mengusir mereka. Setelah itu, dia juga memperingatkanku, "Tidak boleh ada saudari yang masuk ke rumah. Kalau mereka datang lagi, akan kutelepon polisi." Ketika melihat perilaku suamiku makin menjadi-jadi dan terus memaksa, aku pun berpikir, "Bukankah ini berarti dia memaksaku melepaskan imanku? Aku tidak bisa meninggalkan imanku, jadi mungkin aku harus meninggalkannya saja." Namun, kemudian aku berpikir, "Bagaimana bisa aku hidup sendiri setelah meninggalkannya?" Aku benar-benar takut hidup sendiri, dan tidak sanggup meninggalkannya. Beberapa kali, saat suamiku memintaku membantunya bekerja, itu bertepatan dengan waktuku melaksanakan tugas, aku pun selalu memilih untuk menyenangkan suamiku dan meninggalkan tugasku. Kadang-kadang, begitu ada hal kecil saja yang tidak membuatnya senang, dia akan mencela dan mengejekku, hingga suatu hari aku tidak tahan lagi dan membantahnya, kataku, "Kau tahu bahwa percaya kepada Tuhan itu hal baik, jadi kenapa kau terus mempersulitku? Apa salahku menghadiri pertemuan dan melaksanakan tugasku? Bukankah aku yang mengurus semua pekerjaan rumah? Apa kau lebih senang jika aku seperti orang lain, bermain mahyong, berpesta, dan tidak mengurus rumah?" Ketika melihatku membantah, dia pun makin marah, sambil meninggikan nada suaranya, dia melototiku dan dengan galak berkata, "Jangan coba-coba memancingku. Kalau kau benar-benar membuatku kesal, akan kulempar semua barangmu ke luar!" Aku berpikir dalam hati, "Apakah ini orang atau setan? Dia membenci Tuhan dan kebenaran!" Lalu aku teringat akan firman Tuhan: "Orang percaya dan orang tidak percaya sama sekali tidak sesuai; sebaliknya mereka saling bertentangan" (Firman, Jilid 1, Penampakan dan Pekerjaan Tuhan, "Tuhan dan Manusia akan Masuk ke Tempat Perhentian Bersama-sama"). Suamiku tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sekarang kami tidak lagi sejalan dan sejiwa, kami juga memang sudah tak lagi bisa menyatu. Dia terus meningkatkan penganiayaannya terhadap imanku, dan aku sering berpikir untuk meninggalkannya saja, tetapi saat membayangkan hidup sendiri dan terasing setelah bercerai, bahwa aku tidak punya siapa-siapa yang akan melindungiku dari kerasnya hidup, dan bagaimana keluarga yang telah dengan susah payah kubangun akan hancur, aku benar-benar tidak sanggup mengambil keputusan. Di tengah kepedihanku, aku datang ke hadirat Tuhan dalam doa, "Ya Tuhan, makin hari, suamiku makin kejam menganiaya aku. Karena dia, aku terkekang baik saat dalam pertemuan maupun tugasku. Hatiku sangat menderita dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi ini, pelajaran apa yang harus kupetik? Mohon cerahkan, terangi, dan tuntun aku."
Dalam saat teduhku, aku membaca firman Tuhan: "Setelah menikah, ada orang-orang yang siap untuk mengabdikan seluruh upaya mereka untuk kehidupan pernikahan mereka, dan mereka siap untuk berjuang, bergumul, dan bekerja keras untuk pernikahan mereka. Ada orang-orang yang mati-matian mencari uang dan menderita, dan tentu saja, makin menggantungkan kebahagiaan hidup mereka kepada pasangan mereka. Mereka meyakini bahwa apakah mereka akan menjadi bahagia dan gembira atau tidak dalam hidup bergantung pada seperti apa pasangan mereka, apakah mereka yang orang baik atau tidak; apakah kepribadian dan minat mereka cocok dengan dirinya atau tidak; apakah mereka adalah orang yang mampu menafkahi mereka dan mengurus keluarga atau tidak; apakah mereka adalah orang yang dapat menjamin kebutuhan pokok mereka di masa depan, dan menjadikan mereka keluarga yang bahagia, stabil, dan menyenangkan; dan apakah mereka adalah orang yang dapat menghibur mereka atau tidak ketika mereka menghadapi penderitaan, kesengsaraan, kegagalan atau kemunduran. Untuk membuktikan hal-hal ini, mereka memberikan perhatian khusus kepada pasangannya selama mereka hidup bersama. Dengan penuh hati-hati dan saksama, mereka mengamati dan mencatat pemikiran, pandangan, ucapan, dan perilaku pasangannya, setiap gerak-geriknya, serta segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka mengingat secara mendetail segala pemikiran, pandangan, perkataan, dan perilaku yang diperlihatkan pasangannya dalam hidup, sehingga mereka dapat memahami pasangan mereka dengan lebih baik. Demikian juga halnya, mereka berharap untuk dapat dipahami oleh pasangan mereka dengan lebih baik, mereka membiarkan pasangan mereka masuk ke dalam hati mereka, dan mereka membiarkan diri mereka masuk ke dalam hati pasangannya agar mereka dapat lebih membatasi satu sama lain, atau agar mereka dapat menjadi orang pertama yang tampil di hadapan pasangan mereka setiap kali sesuatu terjadi, orang pertama yang membantunya, orang pertama yang berdiri dan mendukungnya, menyemangatinya, dan menjadi pendukungnya yang kuat. Dalam kondisi hidup seperti ini, suami dan istri jarang berusaha untuk mengenali orang seperti apakah pasangannya, hidup sepenuhnya dengan perasaannya terhadap pasangannya, dan menggunakan perasaannya untuk merawat pasangannya, menoleransi, menangani semua kesalahan, kekurangan, dan pengejarannya, bahkan sampai pada titik siap mematuhi semua perintahnya. Sebagai contoh, sang suami berkata, 'Pertemuanmu terlalu lama. Pergi saja setengah jam lalu pulang.' Istrinya menjawab, 'Akan kuusahakan sebaik mungkin.' Benar saja, lain kali saat dia pergi ke sebuah pertemuan, dia hanya tinggal selama setengah jam lalu pulang ke rumah, dan sekarang suaminya berkata, 'Nah, itu yang kusuka. Lain kali, pergi saja dan perlihatkan wajahmu, lalu pulang.' Dia berkata, 'Oh, jadi sebesar itulah kau sangat merindukanku! Baiklah kalau begitu, akan kuusahakan sebaik mungkin.' Benar saja, dia tidak mengecewakan suaminya saat lain kali dia pergi ke sebuah pertemuan, dan pulang ke rumah setelah sekitar sepuluh menit. Suaminya sangat senang dan gembira, lalu berkata, 'Itu lebih baik!' Jika suaminya ingin dia pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat; jika suaminya ingin dia tertawa, dia tidak berani menangis. Suaminya melihatnya membaca firman Tuhan dan mendengarkan lagu pujian sehingga dia membencinya serta merasa jijik, lalu berkata, 'Apa gunanya membaca firman itu dan menyanyikan lagu-lagu itu sepanjang waktu? Bisakah kau tidak membaca firman itu atau menyanyikan lagu-lagu itu saat aku sedang di rumah?' Dia menjawab, 'Baiklah, aku tidak akan membacanya lagi.' Dia tidak berani lagi membaca firman Tuhan atau mendengarkan lagu pujian. Dengan tuntutan suaminya, dia akhirnya mengerti bahwa suaminya tidak suka dia percaya kepada Tuhan atau membaca firman Tuhan, jadi dia menemani suaminya ketika dia sedang berada di rumah, menonton TV bersama, makan, mengobrol, dan bahkan mendengarkan dia melampiaskan keluh kesahnya. Dia akan melakukan apa pun untuk suaminya, asalkan itu membuat suaminya bahagia. Dia menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pasangan. Jadi, kapan dia membaca firman Tuhan? Dia menunggu suaminya keluar, lalu mengunci pintu dan buru-buru mulai membaca. Ketika dia mendengar seseorang di depan pintu, dia segera menyimpan buku itu dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani lagi membacanya. Dan ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa bukan suaminya yang pulang—dia salah sangka, jadi dia terus membaca. Saat dia terus membaca, dia merasa gelisah, dia merasa gugup dan takut, berpikir, 'Bagaimana jika dia benar-benar pulang? Sebaiknya aku tidak membaca lagi untuk saat ini. Aku akan meneleponnya dan menanyakan di mana dia berada dan kapan dia akan pulang.' Jadi, dia menelepon suaminya dan suaminya berkata, 'Aku agak sibuk hari ini, jadi mungkin baru pulang pukul tiga atau empat sore.' Ini menenangkan dirinya, tetapi bisakah pikirannya tetap tenang sehingga dia bisa membaca firman Tuhan? Tidak bisa; pikirannya terganggu. Dia bergegas ke hadapan Tuhan untuk berdoa, dan apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan kepercayaannya kepada Tuhan kurang iman, bahwa dia takut pada suaminya, dan tidak mampu menenangkan pikirannya untuk membaca firman Tuhan? Dia merasa dia tidak boleh mengatakan hal-hal ini, jadi tidak ada apa pun yang bisa dia katakan kepada Tuhan. Namun, kemudian dia memejamkan matanya dan menggenggam kedua tangannya. Dia menjadi tenang dan tidak merasa terlalu bingung, jadi dia membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak memahami firman yang dibacanya. Dia berpikir, 'Sampai di mana aku membaca? Apa yang kupahami dalam perenunganku? Pikiranku benar-benar kacau.' Makin dia memikirkannya, makin dia merasa jengkel dan gelisah: 'Aku tidak mau membaca hari ini. Tidak menjadi masalah jika aku melewatkan saat teduhku sekali ini saja.' Bagaimana menurutmu? Apakah hidupnya berjalan lancar? (Tidak.) Apakah ini penderitaan dalam pernikahan ataukah kebahagiaan pernikahan? (Penderitaan.)" (Firman, Jilid 6, Tentang Pengejaran akan Kebenaran, "Cara Mengejar Kebenaran (11)"). Apa yang Tuhan firmankan benar-benar menggambarkan perilakuku. Aku selalu menganggap pernikahan sebagai tempat yang aman, dan suamiku sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Sejak kecil, aku melihat betapa sulitnya ibuku mengurus rumah tangga seorang diri, sementara ayahku sama sekali tidak membantu, dan aku benar-benar merasa kasihan pada ibuku, jadi aku ingin menemukan pria yang bertanggung jawab dan bisa kuandalkan. Namun, berlawanan dengan harapanku, suami pertamaku ternyata tidak bertanggung jawab dan tidak punya rasa tanggung jawab, kami pun akhirnya bercerai. Setelah itu, aku hidup kesepian, penuh dengan penderitaan dan tanpa dukungan. Kemudian, aku bertemu suamiku yang sekarang, dan dia sangat peduli serta menyayangiku. Aku tidak perlu khawatir soal urusan rumah, dan dia bahkan membayar asuransi untuk anak perempuanku, jadi aku menganggapnya orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Seperti kata pepatah, "Anak sebanyak apa pun tidak sebanding dengan pasangan yang datang di usia senja." Aku pun setuju dengan pepatah ini. Meskipun aku punya seorang putri, bisa jadi kelak aku tidak akan bisa bergantung padanya, jadi aku tetap harus bergantung pada suamiku. Aku menganggap suamiku sebagai sandaranku untuk seumur hidupku, dan tempat yang aman bagiku, jadi demi mempertahankan keluarga ini, aku rela menjalani kesulitan dan kelelahan. Aku menaatinya dalam segala hal agar aku tidak tampak salah di matanya, dan selama kami bisa hidup bersama seperti ini sampai tua, aku sudah merasa puas. Bahkan setelah mengenal Tuhan, aku masih sangat memandang tinggi pernikahan. Saat suamiku terus menghalangi imanku, aku takut pernikahan kami hancur dan kehilangan keluarga ini, jadi aku terus menaatinya. Saat dia melarang para saudari datang untuk menghadiri pertemuan di rumah aku takut bahwa berdebat dengannya akan merusak hubungan kami, jadi aku menaatinya dan berhenti melakukan penerimaan tamu untuk pertemuan di rumah. Jika pertemuan berlangsung terlalu lama, aku khawatir akan terlambat pulang dan menunda memasak untuk suamiku, aku bahkan menyela pemimpin sebelum persekutuannya selesai, mengganggu jalannya pertemuan. Saat tugasku berbenturan dengan keharmonisan keluarga, aku takut suamiku marah lalu hubungan kami menjadi terganggu, jadi aku selalu memilih untuk menyenangkannya dan meninggalkan tugasku. Demi membuat suamiku puas, aku menunda untuk mengejar kebenaran dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Aku tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabku sebagai makhluk ciptaan. Aku menjadikan suamiku sebagai sandaranku dan menaatinya dalam segala hal. Aku senantiasa memperhatikan ekspresinya saat melaksanakan tugasku, dikekang olehnya, serta merasa sangat tertekan dan diperlakukan tidak adil. Itu pernikahan yang penuh masalah, bukan kebahagiaan. Aku pun terus mencari, "Bagaimana seharusnya aku menyikapi pernikahan?"
Kemudian, aku membaca firman Tuhan: "Tuhan telah menetapkan pernikahan untukmu hanya agar engkau dapat belajar memenuhi tanggung jawabmu, belajar hidup dengan damai bersama orang lain dan turut berbagi kehidupan bersama, dan mengalami seperti apa hidup bersama pasanganmu dan belajar bagaimana menangani semua hal yang kauhadapi bersama-sama, membuat hidupmu lebih kaya dan berbeda. Namun, Dia tidak menjerumuskanmu ke dalam pernikahan dan, tentu saja, Dia tidak menjerumuskanmu kepada pasanganmu untuk dijadikan budaknya. Engkau bukanlah budak pasanganmu, dan pasanganmu juga bukan tuanmu. Engkau semua setara. Engkau hanya memiliki tanggung jawab sebagai istri atau suami terhadap pasanganmu, dan jika engkau memenuhi tanggung jawab ini, Tuhan akan menganggapmu sebagai istri atau suami yang memuaskan. Tidak ada apa pun yang dimiliki pasanganmu yang tidak kaumiliki, dan engkau tidak lebih buruk daripada pasanganmu. ... Dalam hubungan jasmaniah, selain orang tuamu, yang paling dekat denganmu di dunia ini adalah pasanganmu. Namun, karena engkau percaya kepada Tuhan, dia memperlakukanmu seperti musuh dan menyerang serta menganiayamu. Dia tidak mau mengizinkanmu untuk menghadiri pertemuan. Jika dia mendengar gosip, dia pulang ke rumah untuk memarahi dan menganiayamu. Meskipun engkau sedang berdoa atau membaca firman Tuhan di rumah dan sama sekali tidak memengaruhi kehidupan normalnya, dia akan tetap memarahi dan menentangmu, dan bahkan memukulimu. Katakan kepada-Ku, orang macam apa ini? Bukankah dia adalah setan? Inikah orang yang paling dekat denganmu? Apakah orang semacam ini pantas untuk membuatmu memenuhi tanggung jawabmu terhadapnya? (Tidak.) Tidak, dia tidak pantas! Jadi, ada orang-orang yang berada dalam pernikahan semacam ini masih mematuhi pasangan mereka, rela mengorbankan segalanya, mengorbankan waktu yang seharusnya mereka manfaatkan untuk melaksanakan tugas, mengorbankan kesempatan untuk melaksanakan tugas mereka, dan bahkan mengorbankan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal ini, dan setidaknya mereka harus melepaskan gagasan-gagasan semacam itu. ... Tujuan Tuhan menetapkan pernikahan adalah agar engkau dapat memiliki pasangan hidup, melewati suka dan duka kehidupan dan melewati setiap tahap kehidupan bersama pasanganmu, sehingga engkau tidak seorang diri atau kesepian dalam setiap tahap kehidupan, memiliki seseorang di sisimu, seseorang yang kepadanya engkau mencurahkan pemikiran terdalammu, dan memiliki seseorang untuk menghibur dan menjagamu. Namun, Tuhan tidak menggunakan pernikahan untuk mengikatmu, atau untuk membelenggumu, sehingga engkau tidak punya hak untuk memilih jalanmu sendiri dan menjadi budak pernikahan. Tuhan telah menetapkan pernikahan untukmu dan mengatur pasangan hidup untukmu; Dia tidak mencarikanmu tuan atas budak, Dia juga tidak ingin engkau terkurung dalam pernikahanmu tanpa memiliki pengejaranmu sendiri, tujuan hidupmu sendiri, tanpa arah yang benar untuk pengejaranmu, dan tanpa hak untuk mengejar keselamatan. Sebaliknya, entah engkau sudah menikah atau belum, hak terbesar yang Tuhan berikan kepadamu adalah hak untuk mengejar tujuan hidupmu sendiri, menentukan pandangan hidup yang benar, dan mengejar keselamatan. Tak ada seorang pun yang dapat mengambilnya darimu, dan tak ada seorang pun yang dapat ikut campur di dalamnya, termasuk pasanganmu" (Firman, Jilid 6, Tentang Pengejaran akan Kebenaran, "Cara Mengejar Kebenaran (11)"). Firman Tuhan sangat menyentuh hatiku. Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan martabat atau integritas karena pernikahan, Dia juga tidak ingin kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita, lalu kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Tuhan pun tidak ingin diri kita terbelenggu oleh pernikahan dan rela menjadi budaknya. Aku harus melepaskan diri dari belenggu pernikahan, dan berhenti dikekang serta dibelenggu oleh suamiku, karena hanya dengan begitulah aku bisa hidup bermartabat dan berintegritas. Aku jelas tahu bahwa percaya kepada Tuhan adalah jalan hidup yang benar, dan melaksanakan tugas adalah tanggung jawab serta kewajiban sebagai makhluk ciptaan, tetapi aku hidup menurut pemikiran dan pandangan yang ditanamkan oleh Iblis. Aku percaya bahwa "Laki-laki adalah kepala rumah tangga," dan "Pernikahan adalah tempat yang aman." Ketika melihat suamiku memperlakukanku dengan baik dalam keseharian, aku menganggapnya sebagai tempat sandaranku. Ketika dia juga melakukan segala cara untuk menganiaya dan menghalangiku menghadiri pertemuan serta melaksanakan tugasku, demi menyenangkan suamiku, aku rela menjadi budaknya. Aku bekerja keras tanpa mengeluh untuk menyiapkan makan tiga kali sehari, selalu memperhatikan ekspresinya, dan aku menaatinya dalam segala hal. Aku terus-menerus mengalah demi dirinya, tetapi dia justru makin menjadi-jadi, terus menghalangi dan menganiayaku. Aku tidak hanya terkekang saat menghadiri pertemuan, tetapi juga gagal melaksanakan tugasku sebagai makhluk ciptaan. Bagaimana bisa aku hidup bermartabat dan berintegritas jika seperti ini? Tuhan menetapkan pernikahan agar manusia mengalami suka dukanya, untuk memperkaya pengalaman hidup mereka, untuk belajar menghadapi orang-orang, peristiwa, dan berbagai hal dalam hidup, serta agar dapat saling mendukung dan menemani sebagai pasangan hidup. Tuhan tidak begitu saja menyerahkanku kepada pernikahan. Aku bukan budak suamiku; kami setara. Namun, demi mempertahankan rumah tangga, aku menaatinya dalam segala hal, melalaikan tugasku, dan hampir kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Aku sungguh bodoh! Sesungguhnya, sebagai istri, aku sudah melakukan semua pekerjaan rumah tangga yang bisa kulakukan, dan aku sudah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang istri, tetapi dia sengaja mencari-cari kesalahan dan menyulitkanku. Padahal, suamiku pernah percaya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, dan dia tahu bahwa aku percaya kepada Tuhan yang benar, tetapi tetap saja dia melakukan segala cara untuk menghalangi dan menganiaya imanku. Saat melihat saudara-saudari datang ke rumah, dia mengusir mereka dan bahkan mengancam akan memanggil polisi untuk menangkap mereka. Dia bahkan ingin menghancurkan buku firman Tuhan. Esensinya adalah setan yang membenci dan menentang Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan dan sedang menapaki jalan menuju kemusnahan, dia juga ingin menyeretku ke neraka bersamanya. Aku melihat dia sangat berniat jahat dan tidak memiliki kemanusiaan. Aku gagal mengenali esensi dirinya, dan malah terus menyerah padanya, hidup tanpa martabat dan integritas hanya demi mempertahankan pernikahan kami. Sungguh menyedihkan! Jika aku tidak segera sadar dan bertobat, dan terus melalaikan tugasku serta mengkhianati Tuhan demi pernikahan ini, aku tidak layak disebut sebagai makhluk ciptaan, dan pada akhirnya, aku hanya akan disingkirkan dan dimusnahkan Tuhan. Setelah memahami hal ini, diam-diam aku mengambil keputusan dalam hati, "Aku tidak akan lagi menyerah kepada suamiku. Jika dia kembali menghalangi imanku, akan kutinggalkan dia lalu menempuh jalanku sendiri, dan aku akan melaksanakan tugasku sebagai makhluk ciptaan."
Pada bulan September 2023, suatu malam, sepulang dari melaksanakan tugasku, suamiku dengan marah berkata, "Kita perlu bicara. Kita masih bisa melanjutkan ini atau tidak?" Aku berkata, "Bisa atau tidak itu tergantung dirimu." Tiba-tiba dia naik pitam dan membentak dengan kasar, "Baik! Percayalah sepuasmu! Akan kubakar semua bukumu!" Sambil berkata begitu, dia mulai membongkar kotak dan laci, dan sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah menarik beberapa buku firman Tuhan serta laptopku. Aku berusaha mengambil kembali laptopku, tetapi dia berbalik dan membantingnya. Itu terlihat seperti penggerebekan polisi, dan watak Iblis dalam dirinya sepenuhnya tersingkap. Aku sangat takut kalau dalam kemarahannya dia benar-benar memusnahkan buku-buku firman Tuhan, jadi aku segera berdoa kepada Tuhan dalam hati. Dia tidak jadi memusnahkan buku-buku itu. Beberapa saat kemudian, dia pergi dengan marah, dan berkata bahwa mulai saat itu dia akan pindah dan hidup sendirian. Aku berlutut dan berseru kepada Tuhan dalam doa, "Tuhan, aku tidak menyangka suamiku sejahat ini. Aku sudah melihat dengan jelas esensi Iblis dalam dirinya, dan aku tidak bisa bertahan dengannya lagi. Pernikahan kami sudah berakhir. Namun kalau aku meninggalkannya, ke mana aku harus pergi? Bagaimana aku bisa hidup sendirian? Aku sangat menderita; tolonglah aku." Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan: "Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai memenuhi tanggung jawabmu. Demi rencana Tuhan dan penentuan-Nya, engkau memainkan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apa pun latar belakangmu, dan apa pun perjalanan yang akan kautempuh, bagaimanapun juga, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan penataan Surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, karena hanya Dia yang berdaulat atas segala sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan semacam itu. Sejak awal mula manusia tercipta, Tuhan selalu melakukan pekerjaan-Nya dengan cara seperti ini, mengelola alam semesta, dan mengarahkan hukum perubahan segala sesuatu dan lintasan pergerakannya. Seperti halnya segala sesuatu, manusia diam-diam dan tanpa sadar dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan; seperti halnya segala sesuatu, manusia tanpa sadar hidup di bawah pengaturan tangan Tuhan. Hati dan roh manusia berada dalam genggaman Tuhan, dan segala sesuatu dalam hidupnya di bawah tatapan mata Tuhan. Entah engkau memercayai semua ini atau tidak, setiap dan segala hal, baik hidup atau mati, akan bergeser, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu" (Firman, Jilid 1, Penampakan dan Pekerjaan Tuhan, "Tuhan adalah Sumber Kehidupan Manusia"). Firman Tuhan membuatku tiba-tiba menyadari bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Yang Berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan memerintah dan mengendalikan segalanya, dan Tuhanlah yang memberi kita kehidupan. Dia memimpin hidup kita sehari-hari, menjaga dan memelihara kita siang dan malam, tak seorang pun bisa hidup tanpa pemeliharaan-Nya, dan hanya Dialah tempat manusia bersandar. Suamiku hanyalah makhluk ciptaan yang tidak berarti, dan seluruh hidupnya pun ada di tangan Tuhan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, apalagi takdirku, jadi bagaimana mungkin aku bisa bersandar padanya? Sama seperti saat aku dahulu ambruk karena sakit—dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang bisa dilakukannya hanyalah berdiri dan khawatir. Namun, saat aku mulai sadar kembali, aku berdoa kepada Tuhan dan perlahan-lahan siuman. Aku juga teringat tetanggaku, yang sudah menikah selama dua puluh tahun dan baik-baik saja. Namun saat sang istri jatuh sakit hingga lumpuh, suaminya hanya merawatnya beberapa hari lalu meninggalkannya begitu saja. Lalu ada keponakanku: Saat awal menikah, dia dan suaminya hampir tidak terpisahkan, tetapi tidak disangka, setelah mereka membuka usaha dan kehidupan mereka membaik, suaminya berselingkuh dan menjadi sosok yang sama sekali berbeda, ketika mereka kemudian bercerai, suaminya bahkan berusaha merebut harta dan rumah mereka. Dari semua fakta ini, aku menyadari bahwa kita memang tidak bisa mengandalkan orang. Namun, aku masih ingin terus bersandar pada suamiku. Aku benar-benar begitu bodoh, buta, dan menyedihkan! Tuhan adalah Tuhanku, Dialah satu-satunya sandaranku, dan berapa banyak penderitaan atau berkat yang dialami seseorang dalam hidupnya, semuanya sudah ditetapkan Tuhan sejak semula. Setelah aku meninggalkan suamiku, bukankah masa depanku juga ada dalam pengaturan Tuhan? Yang perlu kulakukan hanyalah tunduk dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Setelah mengingat ini, hatiku tidak terlalu sakit lagi, dan aku mendapat sedikit iman. Tak lama kemudian, aku menemukan rumah yang cocok, akhirnya aku pun bebas dari kekangan dan belenggu suamiku, dan hidup bebas seorang diri.
Namun kemudian, hatiku masih belum bisa melepaskan sebagian hal. Aku masih tidak mampu menerima bahwa pernikahan yang telah kuperjuangkan dengan susah payah akhirnya hancur seperti ini, dan bahwa aku harus menjalani sisa hidupku sendirian tanpa sandaran ketika tua nanti. Di malam hari, pikiran-pikiran ini memenuhi kepalaku, dan saat memikirkannya, air mata kesedihan pun mengaliri wajahku. Dalam kepedihan dan ketidakberdayaan, aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa, meminta Tuhan membantuku melepaskan diri dari keadaan ini. Aku membaca firman Tuhan. "Dalam segala jenis pernikahan, engkau dapat memiliki pengalaman seperti ini, engkau dapat memilih untuk menempuh jalan yang benar di bawah bimbingan Tuhan, menyelesaikan misi yang telah Tuhan berikan kepadamu, meninggalkan pasanganmu dengan dasar pemikiran seperti ini dan dengan motivasi seperti ini, lalu mengakhiri pernikahanmu, dan ini adalah sesuatu yang patut diberi ucapan selamat. Setidaknya ada satu hal yang patut disyukuri, yaitu engkau tidak lagi menjadi budak pernikahanmu. Engkau telah melepaskan diri dari perbudakan pernikahanmu, dan engkau tidak perlu lagi khawatir, merasa sedih, dan bergumul karena engkau adalah budak pernikahanmu dan ingin membebaskan diri tetapi tidak mampu. Sejak saat itu, engkau telah melepaskan diri, engkau bebas, dan itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu, Kuharap mereka yang pernikahannya sebelumnya telah berakhir dalam penderitaan dan masih diselimuti bayang-bayang masalah ini, dapat benar-benar melepaskan pernikahan mereka, melepaskan bayang-bayang yang ditinggalkannya, melepaskan rasa benci, amarah, bahkan melepaskan penderitaan yang selama ini kaualami, dan tidak lagi merasakan rasa sakit dan amarah karena semua pengorbanan dan upaya yang kaulakukan untuk pasanganmu dibalas dengan perselingkuhan, pengkhianatan, dan cemoohan dari mereka. Kuharap engkau meninggalkan semua itu, bersukacita karena engkau tidak lagi menjadi budak pernikahanmu, bersukacita karena engkau tidak lagi harus melakukan apa pun atau melakukan pengorbanan yang tidak perlu untuk tuan dalam pernikahanmu, dan sebaliknya, di bawah bimbingan dan kedaulatan Tuhan, engkau menempuh jalan yang benar dalam hidup, melaksanakan tugasmu sebagai makhluk ciptaan, dan tidak lagi merasa sedih serta tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja, engkau tidak perlu lagi merasa risau, cemas, atau gelisah tentang pasanganmu atau sibuk memikirkannya, semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Engkau tidak perlu lagi membicarakan masalah pribadimu dengan pasanganmu, tidak perlu lagi dikekang olehnya. Engkau hanya perlu mengejar kebenaran, dan mencari prinsip-prinsip serta landasan dalam firman Tuhan. Engkau sudah bebas dan tidak lagi menjadi budak pernikahanmu. Beruntunglah karena engkau telah keluar dari mimpi buruk pernikahanmu, bahwa engkau telah benar-benar datang ke hadapan Tuhan, tidak lagi dibatasi oleh pernikahanmu, dan engkau memiliki lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, menghadiri pertemuan, dan bersaat teduh. Engkau benar-benar bebas, engkau tidak perlu lagi bertindak dengan cara tertentu tergantung pada suasana hati orang lain, engkau tidak perlu lagi mendengarkan ejekan dari siapa pun, engkau tidak perlu lagi mempertimbangkan suasana hati atau perasaan siapa pun—engkau sedang menjalani kehidupan lajang, bagus! Engkau bukan lagi seorang budak, engkau bisa keluar dari lingkungan di mana engkau memiliki berbagai tanggung jawab yang harus kaupenuhi terhadap orang lain, engkau bisa menjadi makhluk ciptaan sejati, menjadi makhluk ciptaan di bawah kekuasaan Sang Pencipta, dan melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan—betapa indahnya melakukan hal ini dengan murni! Engkau tidak perlu lagi berdebat, khawatir, merepotkan diri, menoleransi, bersabar, menderita, atau marah tentang pernikahanmu, engkau tidak perlu lagi hidup di lingkungan yang menjijikkan dan situasi yang rumit itu. Ini bagus, semua ini adalah hal yang baik, dan semuanya berjalan dengan baik" (Firman, Jilid 6, Tentang Pengejaran akan Kebenaran, "Cara Mengejar Kebenaran (11)"). Firman Tuhan menghangatkan dan menghibur hatiku dalam setiap kalimatnya. Aku membaca bagian firman Tuhan itu sambil berlinang air mata, dan hatiku merasa dikuatkan. Aku bersyukur karena, di bawah bimbingan Tuhan, aku bisa melepaskan diri dari belenggu pernikahan dan melepaskan diri dari kekangan suamiku. Aku bersyukur karena, di bawah bimbingan Tuhan, aku telah menapaki jalan hidup yang benar, dan mulai saat itu, aku bisa dengan tekun melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan serta mengejar kebenaran untuk memperoleh keselamatan. Ini adalah hal yang baik. Aku tidak seharusnya terus berduka atau bersedih karena runtuhnya pernikahanku.
Sekarang, aku bebas dan tidak lagi menjadi budak pernikahan, aku pun tidak lagi dikendalikan atau dikekang oleh suamiku. Saat menghadiri pertemuan, aku tidak lagi harus terburu-buru pulang untuk memasak; aku bisa mengikuti pertemuan selama yang kuinginkan, dan aku bisa pergi melaksanakan tugasku kapan saja aku mau. Hidup bebas itu sungguh menyenangkan! Aku tidak lagi harus dipusingkan, khawatir, atau terbebani oleh kebutuhan sehari-hari suamiku, sekarang aku juga punya lebih banyak waktu untuk mengejar kebenaran, makan dan minum firman Tuhan, serta melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan. Saat ada masalah dalam tugasku, aku bisa menenangkan hatiku, merenung, dan mencari kebenaran untuk mengatasinya, sehingga tugasku pun mulai membuahkan hasil. Aku sekarang punya lebih banyak waktu untuk melakukan saat teduh setiap hari, merenungkan keadaan diriku yang keliru dan segera mencari firman Tuhan untuk mengatasinya, dan aku juga punya waktu untuk menulis catatan saat teduh. Pada saat yang sama, dengan merenungkan firman Tuhan, aku belajar mengenali berbagai jenis orang—mana yang benar-benar orang percaya dan mana pengikut yang bukan orang percaya. Ini semua adalah hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kudapatkan. Dahulu, aku hidup menurut pemikiran dan pandangan Iblis, terlalu mementingkan pernikahan. Aku menganggap suamiku sebagai sandaranku, dan terus mempertahankan pernikahan kami. Aku selalu mengalah, dan hidup dalam penderitaan serta tekanan besar. Tuhanlah yang menuntunku keluar dari belenggu pernikahan, dan Tuhan jugalah yang membuatku mampu membedakan esensi suamiku. Syukur kepada Tuhan!